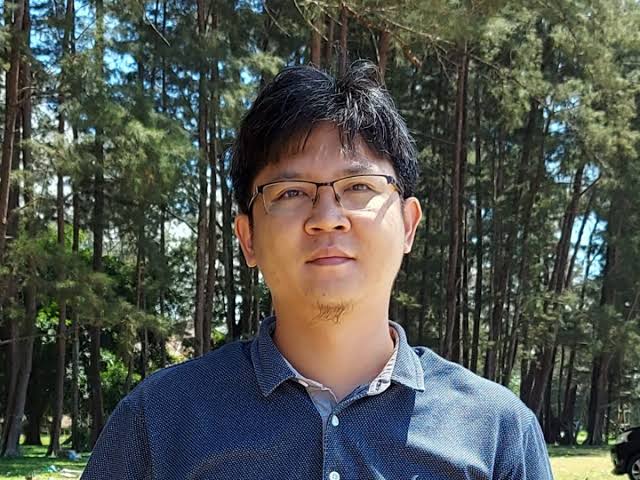Samarinda, Klausa.co – Fenomena politik uang terus menjadi perbincangan hangat dari pemilu ke pemilu. Bagi sebagian besar kalangan, praktik ini bukanlah hal baru, namun dampaknya terhadap jalannya demokrasi tetap menimbulkan kekhawatiran. Herdiansyah Hamzah, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), memaparkan bahwa istilah politik uang pada awalnya memiliki makna yang sangat luas. Istilah ini mencakup segala bentuk transaksi yang melibatkan imbalan, mulai dari suap hingga jual-beli pengaruh.
“Seiring waktu, pengertian ini semakin dipersempit,” jelas Herdiansyah.
Kini, merujuk pada kajian Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, istilah politik uang lebih spesifik dipahami sebagai distribusi uang atau barang oleh kandidat kepada pemilih menjelang pemilihan. Meski begitu, praktik ini tetap menjamur, meski telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Dalam regulasi tersebut, Pasal 187A secara eksplisit melarang tindakan politik uang, baik dari sisi pemberi maupun penerima. Hukuman yang dikenakan tak tanggung-tanggung: penjara minimal 36 bulan dan denda hingga satu miliar rupiah. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Herdiansyah, yang akrab disapa Castro, aturan hukum ini belum memberikan efek jera yang diharapkan.
Menurut catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), selama Pilkada serentak tahun 2020 saja terdapat 262 kasus dugaan politik uang yang telah masuk tahap pengkajian dan penyidikan. Dari jumlah tersebut, enam kasus sudah sampai pada putusan pengadilan, dan semuanya dinyatakan bersalah.
Kasus-kasus ini tersebar di sejumlah daerah, termasuk Kota Tarakan, Kabupaten Berau, Kota Palu, Tangerang Selatan, hingga Cianjur. Fakta ini, menurut Castro, membuktikan bahwa keberadaan delik politik uang dalam UU Pilkada masih jauh dari cukup untuk menghentikan praktik ini.
Tanpa penegakan hukum yang memadai, mustahil akan tercipta efek jera. Begitu argumen Castro, yang juga didukung oleh data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI). Berdasarkan survei terhadap 2.000 responden yang terlibat dalam Pilkada 2020, tercatat 21,9 persen pemilih di tingkat provinsi mengaku pernah ditawari uang atau barang oleh kandidat. Di tingkat kabupaten/kota, angka ini bahkan mencapai 22,7 persen.
“Politik uang semakin hari semakin parah,” tandas Castro.
Keprihatinan ini semakin diperburuk oleh pernyataan sejumlah elit politik yang terkesan menormalisasi praktik politik uang. Salah seorang anggota Komisi II DPR RI bahkan pernah mengusulkan agar politik uang dilegalkan melalui peraturan KPU. Gagasan ini, menurut Castro, sangat keliru. Alih-alih menyelesaikan masalah, pendekatan ini justru menutupi akar persoalan.
Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab suburnya politik uang. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan cenderung lebih pragmatis, menerima tawaran uang sebagai bentuk survival. Pendidikan juga memainkan peran penting. Pemilih dengan tingkat pendidikan rendah lebih rentan terhadap praktik jual-beli suara.
Tak hanya itu, lemahnya elektabilitas dan popularitas kandidat juga seringkali menjadi alasan di balik praktik politik uang. Kandidat dengan popularitas rendah harus mengandalkan uang untuk menarik suara. Kondisi ini mencerminkan krisis kaderisasi di tubuh partai politik, yang gagal melahirkan calon-calon dengan kapasitas unggul dan kedekatan dengan rakyat.
“Krisis ini membuat partai-partai politik hanya mengandalkan orang-orang karbitan yang diorbitkan instan, hanya karena mereka punya modal besar,” tegas Castro. (Nur/Mul/Klausa)